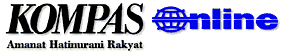
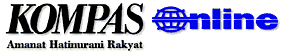
Senin, 8 Juni 1998
SUDAH sering dikemukakan, bahwa usaha mengatasi krisis moneter dan krisis ekonomi melalui reformasi ekonomi hanya dapat dilakukan apabila kita juga melakukan reformasi politik dan reformasi hukum yang diharapkan mampu memulihkan kredibilitas rakyat maupun khalayak internasional.
Akan tetapi, perilaku dan "artifak" ekonomi, politik dan hukum itu dapat "berbunyi" atau bermakna bila diletakkan dalam konteks kultural tertentu, dipahami dalam asumsi-asumsi kultural tertentu. Bahkan perilaku atau artifak tertentu dari salah satu bidang itu dapat diberi makna dan interpretasi berbeda-beda dari satu konteks budaya ke konteks budaya lainnya. Inilah antara lain yang pernah dikemukakan oleh Barsoux dan Scheider, dua pakar administrasi dari lembaga INSEAD, Perancis (Managing Across Cultures, 1997).
Reformasi kultural
Karena pemahaman, penghayatan dan pengamalan bidang hukum, ekonomi dan politik itu ternyata berakar pada kebudayaan (Yang untuk sebagian besar berada pada wilayah blindspot dalam perilaku interaktif kita), maka keberhasilan reformasi ketiga bidang itu juga tergantung pada kerelaan dan kemampuan kita untuk menggali asumsi-asumsi kultural itu dan menyorotinya di wilayah "arena". Begitu kalau kita memanfaatkan peristilahan Johari window dari disiplin psikologi.
Biarpun dari perspektif hukum ada kontroversi antara konstitusional atau tidak konstitusionalnya "serah terima jabatan Presiden" dari HM Soeharto kepada BJ Habibie pada 21 Mei 1998 yang lalu, tilikan kultural mengingatkan kita pada penyerahan takhta seorang raja Mataram kepada sang putra mahkota dalam sebuah sistem pemerintahan monarki. Hal ini makin berbunyi, manakala kita ingat bahwa untuk menetapkan siapa yang akan diajukan sebagai Wakil Presiden, fraksi-fraksi di MPR terlebih dulu berkonsultasi atau bersilaturahmi - atau lebih tepat lagi sowan - kepada sang Bapak yang sudah begitu lama menjadi Presiden, sehingga cenderung menjadi Bapak sebuah dinasti. Hal ini makin berbunyi lagi, ketika idiom lengser keprabon dimasyarakatkan dan diterima sebagai hal yang wajar, biarpun ditilik dari sudut hukum istilah itu juga tidak terdapat dalam konstitusi. Dengan demikian, kita pun layak bertanya apa artinya dan apa manifestasi "uwur-uwur sembur" dalam periode pasca-Soeharto yang disebut-sebut sebagai masa transisi ini.
Dalam bidang ekonomi pun barangkali dapat dikatakan bahwa di samping nepotisme sebagai perwujudan dinasti-isme, kolusi dan korupsi dalam bentuk upeti-isme berakar pula pada blindspot budaya yang sama. Yoshihara Kunio dalam penelitiannya tentang ersatz capitalism sebenarnya dapat menelusuri lebih lanjut asumsi-asumsi kultural yang melahirkan kapitalisme semu itu, sama seperti ketika Weber mengaitkan kapitalisme dengan etos Protestan, atau Bellah mencoba menghubungkannya dengan religi Jepang pada era Tokugawa.
Reaksi dan rekayasa kebencian terhadap para pedagang Tionghoa tampaknya juga berhulu pada titik-buta keratonisme itu, yang secara historis pernah muncul dalam peristiwa "Geger Pecinan" pada akhir era Kartasura. Pada zaman itu, "reformasi" dilakukan antara lain dengan memindah ibu kota dari Kartasura ke hutan Sala di tepi Bengawan yang kemudian dinamai Surakarta (tinggal "dibalik", seperti Kyoto dan Tokyo dalam Keratonisme Jepang). Maka usul untuk memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke Yogyakarta dalam rangka reformasi dapatlah dimengerti dalam konteks kultural ini. Mungkin sebagai guyon (canda) dapatlah diajukan usul tambahan, agar Yogyakarta lebih dahulu diganti namanya menjadi Kartajaya (sebagai "kebalikan" dari Jakarta yang sebenarnya merupakan kependekan dari Jayakarta).
Tugas berat
Maka memang beratlah tugas reformasi kita. Berat, dan membutuhkan napas yang panjang dan stamina yang "joss". Reformasi ekonomi, politik dan hukum tidak akan menghasilkan buah berjangka panjang apabila tidak dilihat sekaligus sebagai sebuah reformasi kultural. Para pelaku reformasi selayaknya berada pada garda depan pencerahan yang sekali lagi membangunkan khalayak ("kebangkitan nasional" dulu kalau tidak salah juga disebut "kebangunan nasional") dari mimpi buruk keratonisme dan segala macam paternalisme yang membungkam dinamika akal budi dan merepresi aktualisasi daya-daya manusia beradab.
Tiadanya perspektif pencerahan, yang berintikan demokrasi dan Hak Asasi Manusia dan kini juga hormat pada lingkungan hidup, hanya akan membuat para reformis mengidap miopia yang pada gilirannya hanya akan mengedepankan kepentingan jangka pendek pribadi, keluarga, golongan, lebih dari kepentingan jangka panjang seluruh bangsa. Tiadanya perspektif kultural, dengan kata lain, hanya akan membuat reformasi menjadi gejala sementara dan keratonisme kembali dalam waktu singkat. Pendek kata, ketiadaan reformasi kultural akan membuat KKN sebagai norma dan reformasi sebagai kekecualian. Pengalaman pahit ini sudah kita alami dalam peralihan Orde Lama dan Orde Baru dalam sejarah negeri kita. Keratonisme yang muncul dari gegap gempita kebaruan itu ternyata lebih intensif, lebih meluas, lebih lama bertahan.
Pengertian "reformasi total" dapat saja diberi makna dalam kaitan dengan agenda politik jangka pendek, artinya bukan hanya "menurunkan" HM Soeharto dari kepresidenan saja. Tetapi reformasi total juga dapat diartikan sebagai reformasi ekonomi, politik, hukum, yang dilakukan dalam rangka perubahan budaya yang berkesinambungan. Usaha ini tidak mungkin semata-mata diletakkan pada pundak Mendikbud atau Menteri Pariwisata beserta segala jajarannya. Perilaku eksekutif, legislatif, yudikatif, bahkan perilaku para oposan, insan kampus dan rakyat seumumnya perlu disoroti dari tilikan kultural ini, sehingga kita semua secara transparan dapat saling mengingatkan dan mengoreksi diri.
Agenda jangka pendek
Meskipun reformasi total adalah usaha budaya yang memerlukan waktu panjang, namun ada saja pekerjaan-pekerjaan rumah kecil yang dapat dimulai sekarang.
Pertama, dalam berinteraksi dan bertegur sapa dengan Presiden kita perlu tetap memperlakukannya sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan sebuah negara Republik modern, bukan sebagai seorang Raja atau Bapak dari sebuah dinasti. Menarik untuk diamati, bahwa enam tokoh oposisi yang sudah kita kenal itu tidak membungkuk-bungkukkan badan sewaktu berjabatan tangan dengan Presiden Habibie. Dalam konferensi pers pun, mereka menyebut BJ Habibie sebagai "Presiden" atau "Presiden Habibie". Sikap mereka itu berbeda sekali dengan Menteri Sekretaris Negara yang masih menggunakan term sapaan pra-reformasi "Bapak Presiden". Sang Presiden itu dalam pertemuan dapat "mengajukan usul" atau "menarik kesimpulan" (seperti dalam bahasa Nurcholish Madjid). Tetapi sang Bapak Presiden akan kembali lagi "memberi petunjuk" (seperti yang selalu mengingatkan kita pada si Bung).
Kedua, proporsi-proporsi atau ungkapan-ungkapan politik yang sifatnya mengaburkan, mengurangi transparansi dan memuat dominasi pemaknaan perlu ditinggalkan. Sebagai contoh adalah ungkapan ngono yo ngono ning ojo ngono yang bahkan masih diucapkan oleh tokoh reformis Menkop dan PPK dalam salah satu acara talkshow di RCTI beberapa waktu lalu (25 Mei 1998). Kalau kata "ngono" kita substitusi dengan "oposisi", maka "persamaan" itu akan berbunyi: oposisi ya oposisi, tetapi jangan oposisi. Hasilnya? Kata "oposisi" diganti dengan kata "penyeimbang", sama dengan "kenaikan harga" diganti dengan "penyesuaian". Masuknya kata "penyeimbang" sebagai entri pertama dalam kamus eufemisme era reformasi adalah salah satu sinyal yang mengecilkan hati, apakah betul reformasi kita ini akan menjadi reformasi total.
Ketiga, dalih atau argumen "tidak sesuai dengan kebudayaan kita" pun perlu dikaji dengan sungguh-sungguh. Malahan seorang Ki Hajar Dewantara yang begitu menjunjung tinggi kebudayaan kita melalui Perguruan Taman Siswa pun tetap merasa perlu memilah-milah, bagian mana dari "kebudayaan kita" yang perlu dipertahankan dan bagian mana yang perlu direformasi. Dalam kaitan ini, dapat kita pertanyakan, apakah penolakan oposisi sebagai hal yang "tidak sesuai dengan kebudayaan kita" itu masih tepat. Dalam kaitan ini, dapat kita persoalkan pula, apakah masih tepat anggapan bahwa tidak mengutik-utik secara hukum mantan seorang Presiden (termasuk mengusut harta kekayaannya) sebagai kebajikan kebudayaan kita, mikul dhuwur mendhem jero.
Pada akhirnya, reformasi kultural memerlukan keberanian dan ketabahan yang lebih besar. Dalam reformasi kultural, kita berhadapan dengan kebiasaan-kebiasaan buruk yang sudah berurat berakar pada diri sendiri, pada diri kita masing-masing. Dalam reformasi kultural, kita harus mempelajari kebiasaan-kebiasaan baru, seperti sikap demokratis, toleran, hormat kepada hak-hak asasi manusia (siapa pun dia) serta hormat kepada lingkungan alamiah kita, yang lebih sesuai dengan tuntutan sebuah zaman baru.
Kalau Pak Sarwono Kusumaatmadja dikabarkan pernah mengibarkan reformasi politik itu dengan "cabut gigi", maka reformasi kultural ini barangkali dapat diibaratkan dengan usaha seorang perokok berat yang berupaya menghentikan kebiasaan yang sudah berurat berakar itu. Dan itu lebih sukar, lebih tidak nyaman, lebih memakan waktu, lebih besar risiko gagal, dari sekadar "cabut gigi".
(Alois A Nugroho, Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Unika Atma Jaya Jakarta.)